“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.”
—Albert Einstein
Setelah melakukan test drive kendaraan asal Jepang yang belum lama dirilis, istri menceritakan kegirangan duo Xi sewaktu ikut berkeliling kompleks bersama seorang staf penjualan dealer terdekat. Intinya tentu saja mereka ingin memiliki mobil seperti itu. Begitu juga kami agar mobilitas tinggi terpenuhi. Begitu dihitung, uang kami memang cukup untuk membayar uang muka dan cicilan hingga beberapa bulan ke depan.
Namun sebagai pekerja lepas, saya pikir menghabiskan uang cukup besar untuk membeli mobil secara kredit jauh dari kata bijak. Tak sedikit orang bilang, punya utang itu enak sebab jadi motivasi untuk lebih giat bekerja. Kami berpandangan sebaliknya, alih-alih bekerja dengan giat, utang justru menghadirkan teror tersendiri dengan berbagai dampak negatif seperti yang pernah terjadi pada Pak Fahmi.
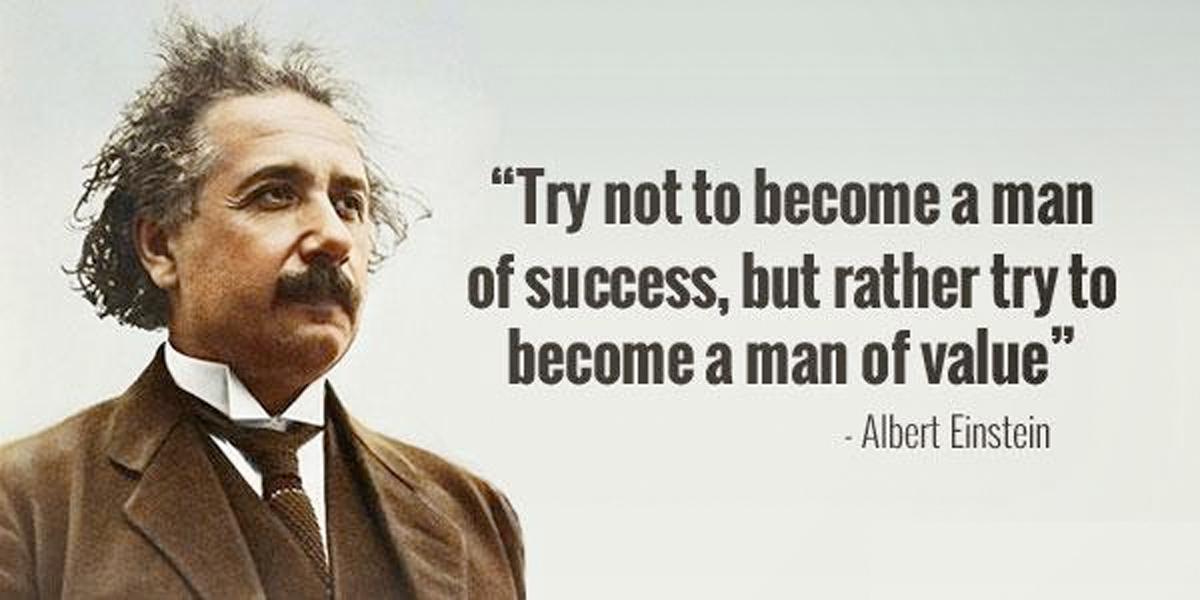
Singkat kata, akhirnya kami urung membeli mobil baru karena harus dalam skema mencicil. Solusinya, kami putuskan akan membeli kendaraan bekas yang masih bagus namun bisa kami bayar secara tunai. Kami pun browsing dan menemukan gerai penjualan tak jauh dari rumah. Mobilnya masih oke, hanya butuh sedikit sentuhan agar prima kembali. Sayang sekali si empunya bertahan pada harga yang tidak kami sepakati.
Musibah bertubi-tubi
Kami lantas pulang dengan alasan akan mempertimbangkan. Siapa tahu beberapa hari ke depan harga masih bisa digoyang. Rupanya tidak, dan kesepakatan pun gagal. Sampai beberapa bulan kemudian Bunda sakit mendadak dan harus dirawat di rumah sakit. Beberapa hari dirawat, ia pun diperbolehkan pulang tanpa ketahuan penyebabnya. Dua hari kemudian dia balik ke rumah sakit yang sama dengan gejala yang mirip. Syukurlah dua hari kemudian Bunda sehat kembali tentunya setelah ditukar dengan harga atas jasa rumah sakit.
Tahun berikutnya giliran si bungsu yang sakit, juga mendadak. Dokter hanya menyebutkan ia terkena infeksi virus yang sampai kami pindah pun tak ketahuan jenisnya. Semula kami menduga ia terserang penyakit kuning, namun bukan. Yang jelas kadar HB turun sangat drastis sampai mengharuskan ia dirawat di ruang HCU (High Care Unit) karena ini satu-satunya ruang intensif yang tersedia di rumah sakit itu. Ruang isolasi di rumah sakit lain habis.
Sudah bisa diduga, selain lelehan air mata melihat si bungsu dikepung oleh tabung oksigen, mesin ECG, dan berbagai treatment khas lainnya, kami harus melepaskan rupiah demi rupiah demi mengembalikan senyumnya. Bukankah memang itu gunanya uang, untuk dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan walau terkadang itu berat? Termasuk berat hati saat kami harus pindah ke kota kelahiran saya walau kami masih sangat betah tinggal di Bogor.
Kenapa oh kenapa?
Sebulan di Lamongan, Bumi dirawat lagi dengan gejala mirip saat di Bogor dulu. Infeksi tanpa sebab pasti. Belakangan kuketahui modus infeksi semacam ini kerap menimpa anak-anak di sini. Biarlah tabungan dikuras, asalkan di bungsu kembali waras. Pernah saya ceritakan bahwa ibu sampai hendak mengusulkan penggantian nama akibat sakit tak jelas ini.
Satu hal yang pasti: saya jadi mikir, apa tujuan Tuhan menurunkan semua ini? Kalau mau bermain prasangka, rasanya segala keperihan harus kami tanggung sementara orang lain atau bahkan saudara kami sendiri diliputi kemudahan. If I had to be frank, saya dan istri tak betah di tempat baru. Kalau bukan karena ibu, saya sudah lama menyerah. Jangankan istri yang lahir dan besar di Jakarta, saya yang lahir dan besar di kota ini saja rasanya tak sanggup melanjutkan hidup. Pikiran saya sumpek, buntu, mandeg. Kondisi sosial, psikologi budaya, dan stigma-stigma banyak sekali yang tidak sejalan pemikiran setelah merantau.
Mungkin ini dampak negatif jadi perantau yang kembali ke kampung halaman. Maka saya harusnya tak perlu kembali. Begitu pikiran saya sering berbisik. Kali lain hati saya bergumam, Kamu yang sekarang merasa suci, merasa lebih baik, merasa tak pantas berada di tempat yang tidak sesuai menurut kamu. Seketika teringatlah pada penggalan ayat 32 dalam Surah An-Najm. Hati jadi makin remuk, hancur berkeping-keping. Limbung, tak tahu harus ngapain. Saya tergoda untuk memprotes: God, what is that you want when all that I want finally came to complete void?
Hati remuk
I don’t flaming belong here! I believe I really don’t. Saya merasa benar-benar tak cocok berada di lingkungan baru. Masih terbius suasana Kota Hujan beserta teman-teman dekat. Tak ada kenalan baru yang menarik, di grup perumahan pun sama saja. I don’t enjoy their jokes. I can’t entertain every notion of their frivolity. I don’t fit the society. Gee, I guess I just don’t belong to the neigborhood, neither to the city. Bingung dan terkatung-katung.
Sampai bulan Agustus ketika Saung Literasi kami buka. Saya menemukan semangat yang pernah redup dan nyaris padam. Lalu masjid perumahan dibuka dan saya mendapat amanah di seksi pendidikan dalam dewan ta’mir masjid. Selain mendapat jatah menjadi imam untuk Subuh, posisi ini memungkinkan saya sesekali mengajarkan mengaji bagi anak-anak saat guru tetap berhalangan. Mau tak mau saya harus menambah hafalan surah, minimal menguasai juz 30 sama seperti yang dilakukan oleh kedua anak kami.
Seorang sahabat berkunjung dan menginap bersama keluarganya di rumah kami pekan lalu. Sejak pindah ke Madiun dari Bogor, dia mengalami hal serupa dan dalam hatinya diam-diam tebersit keinginan untuk bisa menebarkan ilmunya yakni mengajarkan Al-Quran di sore hari karena dahulu itulah yang ia tekuni sewaktu kuliah. Pagi berdagang, sore mengajar. Sungguh ideal walaupun sulit didapat.
Keberuntungan sejati
Belakangan pasutri ini mendapat rezeki nomplok karena dipercaya untuk ikut menjadi tenaga pengajar di mushola tempat tinggalnya. Sang suami mengajarkan kitab, sementara sang istri mengajarkan Al-Quran sesuai jurusannya dulu. Rasanya ada yang hampa ketika ilmu yang kudapatkan tidak bisa dimanfaatkan, begitu ujar si istri sewaktu berada di rumah kami.
Apalagi saat mereka menceritakan seorang temannya yang dulu kaya raya namun lalu jatuh terpuruk sedalam-dalamnya. Saya kebetulan pernah bertemu dengan temannya itu sehingga tahu betapa kayanya dia. Dulu dia sering abai saat panggilan shalat memanggil; nanti deh, entar dulu deh. Tapi pada saat yang sama uang dan hartanya mengalir seolah tiada habisnya. Sampai Allah mencabut semua itu dan ia kini tergerak untuk kembali merapat kepada-Nya.
“Beruntunglah kalian karena mendapat kesempatan mengajar seperti sekarang,” ujar teman pailit itu kepada pasutri teman saya. Pesan itu seolah tepat ditujukan kepada saya saat ini. Saya sering merutuk diri sendiri, lantaran tak punya ini, tak ada itu. Tak jarang menggugat keadaan kenapa mesti pulang kampung sementara teman-teman lain asyik dengan kesuksesan di kota lantaran orangtuanya tak menghendaki mereka kembali dan hidup berdekatan di kota kelahiran masing-masing.
Dulu saya sering marah karena Tuhan memberikan sakit begini dan begitu sehingga membatasi saya mencapai kesuksesan. Namun boleh jadi itu akibat tafsiran yang salah tentang kesuksesan. Kalau melihat pendapat Einstein yang saya kutip di awal tulisan, dia justru menekankan value atau nilai—dan seolah melarang kita jadi orang sukses. Ada yang memaknainya begini: value lebih bersifat outward, yakni kita memberi manfaat atau menciptakan kontribusi bagi lingkungan atau orang lain. Sementara sukses cenderung bersifat inward alias mengalir ke dalam—yakni ketika kita menerima berbagai manfaat atau kenikmatan dari luar untuk kita sendiri.
Mana aksimu?
Terserah apa interpretasi Anda mengenai kutipan dari Einstein itu. Yang jelas kini saya berpikir: I no longer give a shit about what I currently don’t have or what I failed to achieve. Rather, I’m more concerned about what I don’t do whereas I actually am able to do it for the good of other people. Terserah orang punya apa, saya tak mengiri. Mereka sudah mengusahakan sesuai kemampuan. Tak penting lagi apa yang gagal saya miliki saat ini.
Yang jauh lebih mendesak untuk dipikirkan dan sangat memprihatinkan adalah: ketika saya tak memberi manfaat apa-apa padahal saya punya kemampuan untuk itu. Berbagai keterbatasan dan kesulitan di tempat baru memang memuakkan, bikin hati ciut, namun saya mulai merasa bahwa semua ini justru mengantar saya pada hal-hal baik yang sebelumnya tidak saya alami atau dapatkan, seperti mengajar di Saung Literasi, jadi imam shalat, admin NBC, dan kesanggupan untuk terus ngeblog.
Menutup tulisan ini, saya teringat ucapan Umar ibn Khattab yang juga pernah saya unggah di blog ini ketika istri tengah dirawat di rumah sakit. Umar malah mengucapkan tahmid sebanyak empat kali ketika dilanda musibah. Begini alasannya: hamdalah yang pertama adalah karena Allah tidak menurunkan musibah yang lebih besar dari itu, padahal Allah pasti sanggup melakukannya. Rasa syukur kedua adalah karena Allah tidak memberikan ujian dalam soal agama. Menurut Umar, musibah apa pun di luar urusan agama terasa kecil. Hamdalah ketiga karena Allah memberinya kesabaran karena dengan kesabaran kita bisa diganjar dengan surga. Syukur keempat, Allah masih memberikan taufik untuk mengevaluasi diri. Taufik sungguh sangat penting bagi seorang muslim. Umar menegaskan, “Demi Allah, selama aku masih menjadi muslim, tak peduli aku pada apa pun yang menimpa diriku.”
Sudah selayaknya saya meraup semangat Umar dalam ucapannya kalau benar saya mengidolakannya. Saya harus bergerak dengan optimisme. Tak ada jaminan bahwa orang yang selalu mendapat kemudahan dan kenikmatan adalah mulia di sisi Allah. Sebaliknya, yang kerap dilanda kesulitan atau keterbatasan belum tentu dihukum oleh Allah. Baik kemudahan atau kesulitan, kekayaan atau kemiskinan, keberlimpahan atau kekurangan, kesuksesan atau kegagalan: seluruhnya adalah ujian sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Fajr.
Dari situlah saya lantas menulis semacam kredo yang menjadi patokan sejak ini. Saya merumuskannya setelah mendapatkan sejumlah kemenangan lomba menulis blog yang justru harus membuat saya wawas diri, bukan menepuk dada bahwa semua kenikmatan ini adaah konfirmasi bahwa saya memang dicintai-Nya.
Hidup bukan soal kesempurnaan, melainkan pengabdian sesuai kemampuan.
Bukan soal kemudahan, tapi kenikmatan memperjuangkan setiap pilihan
Bukan soal nama besar atau penghormatan, tapi keberanian mengambil peran dan memberi arti bagi perbuatan
Bukan soal rupawan, melainkan keikhlasan
Bukan soal prestasi, tapi sumbangsih dan aksi
Bukan tentang gengsi, melainkan fungsi dan kontribusi
Hidup bukan soal menjadi, tetapi usaha untuk terus berbagi
Bukan soal kebanggaan memiliki, tapi keajekan memberdayakan potensi
Hidup bukan kompetisi untuk mengalahkan, tapi sinergi untuk saling menguatkan
Hidup berarti upaya, bukan hasil semata-mata.
Pada akhirnya, jika setiap kemudahan justru membuat kita abai dan jauh dari Tuhan, apalah artinya? Sebaliknya, jika segenap kesulitan malah mendekatkan kita kepada Tuhan, apa lagi yang harus kita khawatirkan? Pernahkah BBC Mania mendengar nikmat dalam bentuk niqmah? Kuncinya: bersyukur, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saya yakin BBC Mania sudah tahu bagaimana caranya.

Merinding membacanya. Suskes selalu untuk Pak Ustadz Masjid Baitur Rahmad, Perumaham Setara, Lamongan.
LikeLike
Kapan ngopi di Aroma?
LikeLike
Suka dengan kalimat ini : Hidup bukan soal kesempurnaan, melainkan pengabdian sesuai kemampuan. Yes, tentu saja. Hidup sejatinya adalah seberapa banyak yang bisa kita beri (untuk masyarakat, bangsa, orang lain, dll)
LikeLike
Betul, Kanghar. Berusaha menciptakan manfaat yang nanti kita panen. Terima kasih sudah mampir ke sini dan salam kenal 🙂
LikeLike
Blog walking pertama tahun 2019, membaca tulisan pak Rudi jadi lebih semangat lagi nig.
setuju sekali, becoming a man of value is greater than a man of success.
Btw, saya juga asli Lamongan (Glagah), tapi merantau di Depok. 🙂
LikeLike
Salam kenal, Mas. Tinggal di Depok daerah mana? Istri saya juga dari Depok. Kalau pas mudik, silakan mampir ke rumah 🙂
LikeLike
Saya di Gandul, Cinere. . Pasti menyenangkan kalau bisa silaturahim dengan penulis inspiratif seperti njenengan.
LikeLike
Semga bisa kopdar suatu hari nanti, Mas.
LikeLike
Sangat inspiratif tulisannya dan sepertinya seorang teman saya yang lain pernah berpendapat demikian dipenghujung tahun lalu, saya kutip sedikit kata-katanya ” jika kita berharap maka kita ketidaknyamanan akan kita rasakan karena harapan adalah keinginan yang belum tentu sama dengan harapan kiita” demikian ungkapannya, selamat berkarya
LikeLike
Terima kasih sudah mampir ke sini, Mas. Sekali-kali bawa nasi liwetnya dong hehe 🙂
LikeLike
Insya Allah kalau panjenengan kunjung ke Bogor akan dibawakan oleh-oleh nasi liwet + rendang jengkol…😁
LikeLike
Terima kasih, Mas. Dapur liwet ini lokasinya di mana ya? Semoga bisa kopdar pas saya ke Bogor,
LikeLiked by 1 person
Ya sudah kalau ke bogor kabar-kabari
LikeLike